1. PEMERIKSAAN MAKROSKOPIS
Pemeriksaan makroskopik tinja meliputi pemeriksaan jumlah, warna, bau, darah, lendir dan parasit.1-4
a. jumlah
Dalam keadaan normal jumlah tinja berkisar antara 100-250gram per hari. Banyaknya tinja dipengaruhi jenis makanan bila banyak makan sayur jumlah tinja meningkat.2,3
b. konsistensi
Tinja normal mempunyai konsistensi agak lunak dan bebentuk. Pada diare konsistensi menjadi sangat lunak atau cair, sedangkan sebaliknya tinja yang keras atau skibala didapatkan pada konstipasi. Peragian karbohidrat dalam usus menghasilkan tinja yang lunak dan bercampur gas.2,3
- Warna
Tinja normal kuning coklat dan warna ini dapat berubah mejadi lebih tua dengan terbentuknya urobilin lebih banyak. Selain urobilin warna tinja dipengaruhi oleh berbagai jenis makanan, kelainan dalam saluran pencernaan dan obat yang dimakan. Warna kuning dapat disebabkan karena susu,jagung, lemak dan obat santonin. Tinja yang berwarna hijau dapat disebabkan oleh sayuran yang mengandung khlorofil atau pada bayi yang baru lahir disebabkan oleh biliverdin dan porphyrin dalam mekonium.3,4 Kelabu mungkin disebabkan karena tidak ada urobilinogen dalam saluran pencernaan yang didapat pada ikterus obstruktif, tinja tersebut disebut akholis. Keadaan tersebut mungkin didapat pada defisiensi enzim pankreas seperti pada steatorrhoe yang menyebabkan makanan mengandung banyak lemak yang tidak dapat dicerna dan juga setelah pemberian garam barium setelah pemeriksaan
radiologik. Tinja yang berwarna merah muda dapat disebabkan oleh perdarahan yang segar dibagian distal, mungkin pula oleh makanan seperti bit atau tomat. Warna coklat mungkin disebabkan adanya perdarahan dibagian proksimal saluran
pencernaan atau karena makanan seperti coklat, kopi dan lain-lain. Warna coklat tua disebabkan urobilin yang berlebihan seperti pada anemia hemolitik. Sedangkan warna hitam dapat disebabkan obat yang yang mengandung besi, arang atau bismuth dan mungkin juga oleh melena.1-4
d. bau
Indol, skatol dan asam butirat menyebabkan bau normal pada tinja. Bau busuk didapatkan jika dalam usus terjadi pembusukan protein yang tidak dicerna dan dirombak oleh kuman. Reaksi tinja menjadi lindi oleh pembusukan semacam itu. Tinja yang berbau tengik atau asam disebabkan oleh peragian gula yang tidak dicerna seperti pada diare. Reaksi tinja pada keadaan itu menjadi asam.2,3
e. darah
Adanya darah dalam tinja dapat berwarna merah muda,coklat atau hitam. Darah itu mungkin terdapat di bagian lua rtinja atau bercampur baur dengan tinja. Pada perdarahan proksimal saluran pencernaan darah akan bercampur dengan tinja dan warna menjadi hitam, ini disebut melena seperti pada tukak lambung atau varices dalam oesophagus. Sedangkan pada perdarahan di bagian distal saluran pencernaan darahterdapat di bagian luar tinja yang berwarna merah muda yang dijumpai pada hemoroid atau karsinoma rektum.2,3,4
f. lendir
Dalam keadaan normal didapatkan sedikit sekali lendir dalam tinja. Terdapatnya lendir yang banyak berarti ada rangsangan atau radang pada dinding usus. Kalau lendir itu hanya didapat di bagian luar tinja, lokalisasi iritasi itu mungkin terletak pada usus besar. Sedangkan bila lendir bercampur baur dengan tinja mungkin sekali iritasi terjadi pada usus halus. Pada disentri, intususepsi dan ileokolitis bisa didapatkan lendir saja tanpa tinja.2,3
g. parasit
Diperiksa pula adanya cacing ascaris, anylostoma dan lain-
lain yang mungkin didapatkan dalam tinja.
2. PEMERIKSAAN MIKROSKOPIS
Pemeriksaan mikroskopik meliputi pemeriksaan protozoa, telur cacing, leukosit, eritosit, sel epitel, kristal dan sisa makanan. Dari semua pemeriksaan ini yang terpenting adalah pemeriksaan terhadap protozoa dan telur cacing.
a. Protozoa
Biasanya didapati dalam bentuk kista, bila konsistensi tinja cair baru didapatkan bentuk trofozoit.
gambar protozoa pada mikroskopis tinja ( sumber : google )
b. Telur cacing
Telur cacing yang mungkin didapat yaitu Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Strongyloides stercoralis dan sebagainya.2,3
telur Ascaris lumbricoides (sumber:google) telur cacing tambang (sumber:google)
c. leukosit
Dalam keadaan normal dapat terlihat beberapa leukosit dalam seluruh sediaan. Pada disentri basiler, kolitis ulserosa dan peradangan didapatkan peningkatan jumlah leukosit.2,3Eosinofil mungkin ditemukan pada bagian tinja yang berlendir pada penderita dengan alergi saluran pencenaan.3
d. eritrosit
Eritrosi thanya terlihat bila terdapat lesi dalam kolon, rektum atau anus. Sedangkan bila lokalisasi lebih proksimal eritrosit telah hancur. Adanya eritrosit dalam tinja selalu berarti abnormal.
f. epitel
Dalam keadaan normal dapat ditemukan beberapa sel epite lyaitu yang berasal dari dinding usus bagian distal. Sel epitelyang berasal dari bagian proksimal jarang terlihat karena sel inibiasanya telah rusak. Jumlah sel epitel bertambah banyak kalau ada perangsangan atau peradangan dinding usus bagian distal.1-3
g. kristal
Kristal dalam tinja tidak banyak artinya. Dalam tinja normal mungkin terlihat kristal tripel fosfat, kalsium oksalat dan asam lemak. Kristal tripel fosfat dan kalsium oksalat didapatkan setelah memakan bayam atau strawberi, sedangkan kristal asam lemak didapatkan setelah banyak makan lemak. Sebagai kelainan mungkin dijumpai kristal Charcoat Leyden Tinja LUGOL Butir-butir amilum dan kristal hematoidin. Kristal Charcoat Leyden didapat pada ulkus saluran pencernaan seperti yang disebabkan amubiasis. Pada perdarahan saluran pencernaan mungkin didapatkan kristal hematoidin.2,3
kristal hemetoidin (sumber:google)
h. Sisa makanan
Hampir selalu dapat ditemukan juga pada keadaan normal, tetapi dalam keadaan tertentu jumlahnya meningkat dan hal ini dihubungkan dengan keadaan abnormal. Sisa makanan sebagian berasal dari makanan daun-daunan dan sebagian lagi berasal dari hewan seperti serat otot, serat elastisdan lain-lain. Untuk identifikasi lebih lanjut emulsi tinja dicampur dengan larutan lugol untuk menunjukkan adanya amilum yang tidak sempurna dicerna. Larutan jenuh Sudan IIIatau IV dipakai untuk menunjukkan adanya lemak netral seperti pada steatorrhoe.2 Sisa makanan ini akan meningkat jumlahnya pada sindroma malabsorpsi.
3. PEMERIKSAAN KIMIA TINJA.
Pemeriksaan kimia tinja yang terpenting adalah pemeriksaan
terhadap darah samar. Tes terhadap darah samar untukmengetahui adanya perdarahan kecil yang tidak dapat dinyatakan secara makroskopik atau mikroskopik.2,3,4 Adanya darah dalam tinja selalau abnormal. Pemeriksaan darah samar dalam tinja dapat dilakukan dengan menggunakan tablet reagens. Prinsip pemeriksaan ini hemoglobin yang bersifat sebagai peroksidase akan menceraikan hidrogen peroksida menjadi air dan 0 nascens (On). On akan mengoksidasi zat warna tertentu yang menimbulkan perubahan warna 4,5
Tablet Reagens banyak dipengaruhi beberapa faktor terutama pengaruh makanan yang mempunyai aktifitas sebagai peroksidase sering menimbulkan reaksi positif palsu seperti daging, ikan sarden dan lain lain. Menurut kepustakaan, pisang dan preparat besi seperti ferrofumarat dan ferro carbonat dapat menimbulkan reaksi positif palsu dengan tablet reagens. Maka dianjurkan untuk menghindari makanan tersebut diatas selama 3-4 hari sebelum dilakukan pemeriksaan darah samar.4,5 Pemeriksaan bilirubin akan beraksi negatif pada tinja normal,karena bilirubin dalam usus akan berubah menjadi urobilinogen dan kemudian oleh udara akan teroksidasi menjadi urobilin. Reaksi mungkin menjadi positif pada diare dan pada keadaan yang menghalangi perubahan bilirubin menjadi urobilinogen, seperti pengobatan jangka panjang dengan antibiotik yang diberikan peroral, mungkin memusnakan flora usus yang menyelenggarakan perubahan tadi.1,2,3 Dalam tinja normal selalu ada urobilin. Jumlah urobilin aka nberkurang pada ikterus obstruktif, jika obstruktif total hasil tes
menjadi negatif, tinja berwarna kelabu disebut akholik. Penetapan kuantitatif urobilinogen dalam tinja memberikan hasil yang lebih baik jika dibandingkan terhadap tes urobilin,karena dapat menjelaskan dengan angka mutlak jumlah
urobilinogen yang diekskresilkan per 24 jam sehingga bermakna
dalam keadaan seperti anemia hemolitik dan ikterus obstruktif.2
Tetapi pelaksanaan untuk tes tersebut sangat rumit dan sulit, karena itu jarang dilakukan di laboratorium. Bila masih diinginkan penilaian ekskresi urobilin dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan urobilin urin.
DAFTAR PUSTAKA
1. Bauer JD, Ackerman PG, Toro G. Clinical Laboratory Methods, 8
ed, Saint Louis : The CV Mosby Company. p. 538.
2. Gandasoebrata R. Penuntun Laboratorium Klinic, cetakan k-4
Penerbit Dian Rakyat 1970; p 152.
3. Hepler OE, Manual of Clinical Laboratory Methods, 4
ed. SprinfieldIllinois USA: Charles C Thomas Publisher 1956; p 124.
4. Hyde TA, Mellor LD, Raphael SS. Gastrointestinal tract in
MedicalLaboratory Technology.
ed, Raphael SS, Lynch, MJG (eds),Philadelphia: WB Saunders Company, 1976: p. 209.
5. Hematest, Leaflet ; Ames Company, Division Miles Laboratory

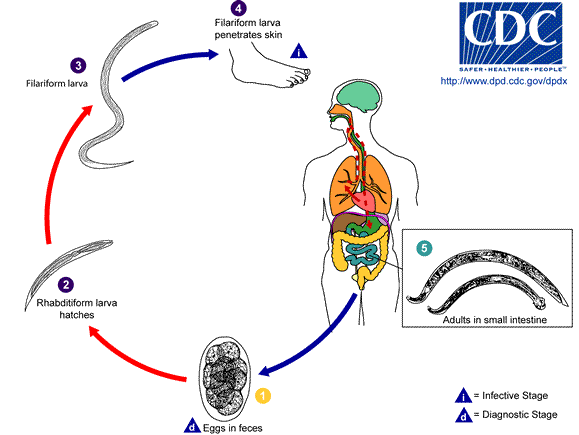 s
s

 s
s



















